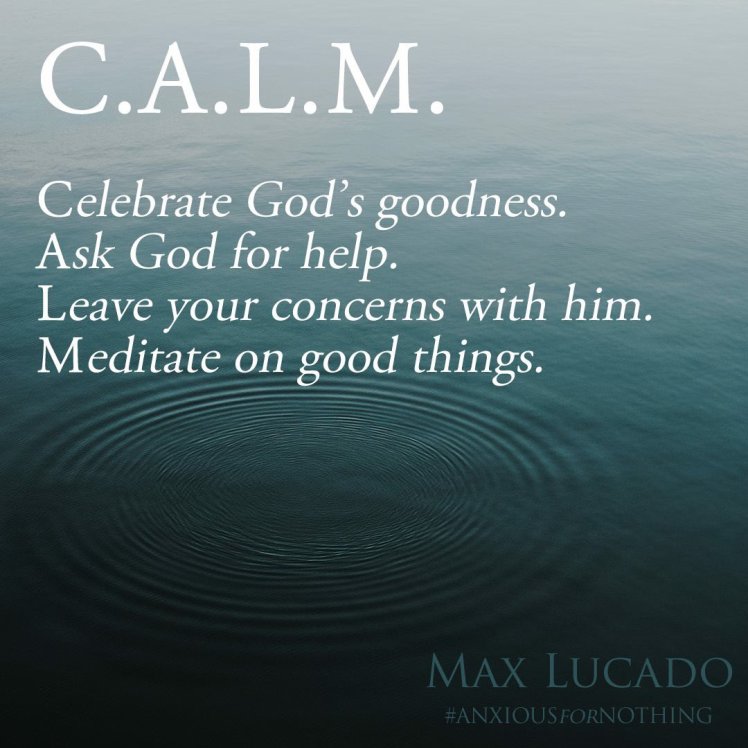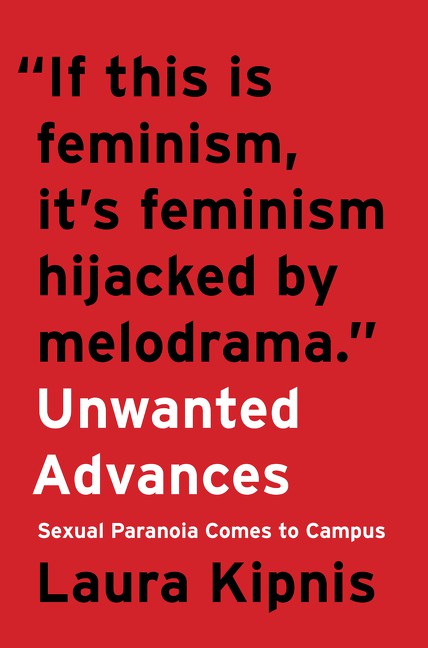Oleh Nur Ahmad*

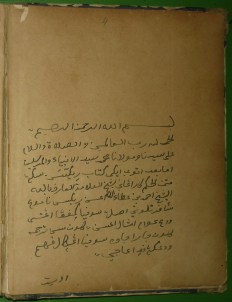
Kenalkah Anda dengan Kiai Muhammad Soleh bin Umar as-Samarani (1820-1903 M)? Tahukah Anda apa sumbangan terbesar Maha-guru Ulama Jawa ini bagi warga bangsa Indonesia? Bagi penulis jawabannya adalah pemikirannya tentang anti-kolonialisme. Dilahirkan di keluarga pendukung Pangeran Diponegoro, dan selalu dalam lingkungan yang demikian, menjadi fondasi bagi Kiai Soleh Darat untuk mengembangkan pandangan anti-kolonialisme Belanda hampir di semua karyanya.
Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830), para kiai pada masa itu menarik diri dari perang fisik dan kembali ke peperangan gagasan dan pemikiran (war of ideas). Sikap ini juga menjadikan fokus ulama kembali untuk meningkatkan pemahaman keislaman di antara masyarakat umum. Agenda perlawanan terhadap Hindia-Belanda yang terus-menerus berusaha memisahkan masyarakat dari agama mereka dilawan dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya ajaran agama bagi kehidupan mereka. Kiai Soleh Darat adalah termasuk yang ikut menjadi pelaku utama dalam perang ide dan kebudayaan ini.
Cara pertama yang dilakukan Kiai Soleh adalah dengan mempropagandakan kembali konsep pembeda antara penindas dan yang ditindas.[1] Merujuk kepada sebuah hadis Nabi Muhammad, Kiai Soleh mendeklarasikan ke-haram-an bagi kaum muslim meniru cara berpakaian orang Eropa (baca Belanda).[2] Beliau berkata, “Beberapa ‘ulama al-muḥaqqiqīn menyebutkan bahwa barang siapa berpakaian selain dengan pakaian yang biasa dikenakan kaum muslim seperti jas, topi, dan dasi, maka ia dinilai sebagai murtad.”[3] Bahkan bukan hanya dalam berpakaian, kaum muslim juga dilarang meniru segala tingkah laku yang khusus dilakukan di Budaya Barat.[4] Sikap ini diikuti oleh muridnya, KHR. Asnawi Kudus yang suatu ketika dengan sangat marah menarik dasi yang dikenakan oleh seseorang di pertemuan nasional Ansor.[5]
Usaha lain dari Kiai Soleh adalah dengan menjauhkan kaum muslim dari menjalin hubungan sebagai bawahan dengan Kolonial-Belanda. Kiai Soleh menetapkan bahwa seorang santri yang menjadi pegawai pemerintah Belanda sama dengan menjadi “pembantu berlangsungnya pemerintahan yang zalim” (khādim al-ẓulmah), dan hal itu merupakan suatu dosa besar.[6] Dalam rangka mencegah santrinya menjadi pembantu di pemerintahan Hindia-Belanda, beliau menyatakan bahwa haram bagi ulama mengajarkan santri yang secara terang-terangan berniat dengan ilmu fikih yang didapatkannya untuk menjadi seorang penghulu di pengadilan agama di pemerintahan Kolonial-Belanda.[7] Beliau menilai tujuan duniawi ini bertentangan dengan tujuan yang diajarkan oleh agama Islam dan semangat memerdekakan warga pribumi yang beliau rintis.
Selain itu, Kiai Soleh juga berusaha sekuat tenaga membentengi kaum wanita dari perilaku keji dan amoral yang ditunjukkan banyak dari orang Eropa di Jawa ketika itu. Misalnya, dalam sebuah makalah Ricklef yang mengutip G. Bruckner menjelaskan bahwa sebagian alasan dari munculnya sikap keras dari kaum muslim di Semarang terhadap orang Eropa adalah sikap immoral mereka.[8] Contoh lainnya, dalam suratnya, Raden Adjeng Kartini mendeskripsikan kebiasaan tak beretika yang terjadi di antara wanita pribumi dengan laki-laki Eropa, termasuk meminum arak.[9] Dalam konteks ini, Suhandjati menyimpulkan bahwa untuk menghindari dampak budaya “baru” ini di masyarakat umum, Kiai Soleh memerintahkan orang tua tidak mengajari putri mereka menulis dengan aksara Latin, yang sangat mungkin akan menjadi media berkomunikasi orang-orang Eropa dengan warga pribumi.[10]
Bahkan Kiai Soleh juga dikabarkan ikut mengusahakan intervensi politik dari Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1883, Konsul Belanda di Jeddah mengabarkan bahwa seorang bernama Soleh dari Semarang meminta Kekhalifahan Turki Utsmani untuk melawan Hindia-Belanda di Jawa.[11]
Kesimpulan yang dapat kita tarik di sini adalah pandangan anti-Belanda yang Kiai Soleh kembangkan didasarkan murni pada kajiannya yang mendalam di bidang ilmu Fikih. Metode tersebut sangat terikat kuat dengan konteks masyarakat tempat pandangan itu lahir, sehingga kondisi sosial masyarakat menjadi konsideran utama, misalnya penggunaan aksara Latin di masyarakat ketika itu. Dengan bersandar pada fondasi yang demikian, dalam kondisi masyarakat yang berbeda, maka hasil kesimpulan hukum dapat berubah. Misalnya, KHR. Asnawi memberikan padangan baru di masa kemerdekaan dengan mengizinkan kaum muslim memakai jas dan dasi karena mengikuti teladan dari Kiai Abdul Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama.[12]
Selain itu, pemikiran anti-kolonialisme dari Kiai Soleh pada akhirnya berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya salah satu muridnya, Hadratusysyaikh Hasyim Asy’ari, dalam menggelorakan cinta tanah air di hati sanubari para santri dan muslimin pada umumnya. Dengan jejak pemikiran yang demikian, maka wajarlah sebagian pencintanya mengusahakan Kiai Soleh untuk diakui sebagai pahlawan bangsa ini, Bukan?
Bibliography
Bruinessen, Martin Van. “Saleh Darat.” dalam Dictionnaire Biographique Des Savants et Grandes Figures Du Monde Musulman Périphérique, Du XIXe Siècle À Nos Jours ed. Marc Gaborieau et al., vol. 2 (Paris: CNRS-EHESS, 1998): 25–26.
Hakim, Taufiq. Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M. Yogyakarta: Indes Publishing, 2016.
Mas’ud, Abdurrachman. Dari Haramain Ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2006.
———. “The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teachings (1850-1950).” PhD diss., University of California. ProQuest (UMI 9714238), 1997.
Ricklefs, Merle Calvin. “The Middle East Connection and Reform and Revival Movements among the Putihan in the 19th-century Java.” dalam Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement and the Longue Duree. Diedit oleh Eric Tagliacozzo. Singapore: NUS Press, 2009: 111-134.
Salim, Abdullah. Majmūàt al-Syarīát al-Kāfiyat li al-‘Awwām Karya Syaikh Muhammad Shalih ibn Úmar al-Samarani: Suatu Kajian Terhadap Kitab Fiqih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19. PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1994.
Soleh as-Samarani, Muhammad. Majmū‘at al-Sharī‘at al-Kāfiyat li al-‘Awwām. Semarang: Toha Putera, n.d.
———. Minhāj al-Atqiyā’ fī Sharḥ Ma‘rifat al-Adhkiyā’ Ilā Ṭarīq al-Awliyā’. Bombay: Maṭba‘at al-Karīmī, 1325.
Suhandjati, Sri. Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya: Studi Terhadap Kitab Majmu’at Karya Kiai Saleh Darat. Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010.
Toer, Pramoedya Ananta. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara, 2003.
*Mahasiswa Master’s di Vrije University Amsterdam, Wakil Sekretaris PCINU Belanda 2017-2019, dan santri PP. Al-Itqon, Bugen, Semarang. Url Facebook: https://web.facebook.com/profile.php?id=100012290461379. Whatsapp: +6285713914707.
[1] Kiai Soleh menyadari betul pentingnya politik identitas yang secara tegas memisahkan identitas dua pihak yang bersengketa dalam rangka membangkitkan semangat perlawanan (resistance identity). Taufiq Hakim, Kiai Soleh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M (Yogyakarta: Indes Publishing, 2016), 121–22.
[2] Yaitu hadis laisa minnā man tasyabbah bi ghoirinā (Bukanlah termasuk golongan kami [kaum muslim, ed.] siapa yang menyerupai selain kami).
[3] Salim, Majmūàt al-syarīát, 202; Soleh as-Samarani, Majmūàt, 24–25.
[4] Hal ini meliputi cara berpakaian, makan, berkomunikasi, dan menyapa (greetings). Soleh as-Samarani, Majmūàt, 25–26.
[5] Mas’ud, Dari Haramain Ke Nusantara, 218.
[6] Soleh as-Samarani, Minhāj al-Atqiyā’, 67.
[7] Sikap ini secara tegas diikuti oleh Kiai Asnawi Kudus, murid Kiai Soleh. Pada tahun 1927 Kiai Asnawi ditunjuk untuk menempati posisi penghulu, namun secara sopan beliau tolak. Abdurrachman Mas’ud, “The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teachings (1850-1950)” (PhD diss., University of California, ProQuest [UMI 9714238], 1997), 208. Kiai Asnawi dikenal sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Selain fatwa-fatwa beliau yang meneruskan sikap Kiai Soleh, Kiai Asnawi juga mengikuti Kiai Soleh dalam menulis karya Pegon yang ditujukan utamanya bagi pendidikan masyarakat umum. Lebih lanjut mengenai peran Kiai Asnawi dalam pengembangan Islam traditional di Indonesia lihat Mas’ud, “The Pesantren Architects”, 188–210.
[8] Ricklefs, “The Middle East Connection”, 113.
[9] Pramoedya Ananta Toer, Panggil aku Kartini saja (Jakarta: Lentera Dipantara, 2007), 155–56; Sri Suhandjati, Mitos Perempuan Kurang Akal Dan Agamanya: Studi Terhadap Kitab Majmu’at Karya Kiai Saleh Darat (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010), 56.
[10] Soleh as-Samarani, Majmūàt, 178; Suhandjati, Mitos Perempuan, 55–56.
[11] Bruinessen, “Saleh Darat.” Melalui komunikasi personal pada 27Januari, 2017, Bruinessen menyebutkan bahwa sumber bagi informasi ini adalah the Algemeen Rijksarchief ARA di Den Haag. Melaliu komunikasi personal dengan K.H. Fathhurrahman Jembrana Bali, beliau juga mengaku pernah mendengar berita tersebut. Namun beliau tidak ingat lagi dari siapa berita itu beliau dapatkan.
[12] Mas’ud, Dari Haramain Ke Nusantara, 218.
Telah terbit pertama kali di NU Online.
Advertisements Share this: